BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Berkembangnya agroindustri hasil perikanan
selain membawa dampak positif, yaitu sebagai penghasil devisa, memberikan nilai
tambah dan penyerapan tenaga kerja, juga telah memberikan dampak negatif yaitu
berupa buangan limbah. Limbah hasil dari kegiatan tersebut dapat berupa limbah
padat dan limbah cair (Ibrahim, 2005). Limbah perikanan ini semakin meningkat
karena adanya peningkatan konsumsi manusia untuk sumberdaya perikanan sehingga
berbanding lurus dengan banyaknya limbah perikanan yang dihasilkan. Limbah perikanan
yang dihasilkan berupa kulit, tulang, kepala, ekor dan jeroan. Dari
hasil survei yang dilakukan dapat diperkirakan volume limbah ikan setiap
nelayan di wilayah tangkap perairan Indonesia sekitar satu kilogram per hari
sehingga tersedia 1.600 kilogram limbah padat ikan setiap hari (Prihatiningsih et al., 2014).
Indonesia merupakan
Negara yang terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah. Namun sayang, di Indonesia
masakan laut dan pengolahan hasil laut dari Cructaceae belum dapat
optimal. Pada umumnya sebagian besar pengolahan hasil laut dari Cructaceae hanya
digunakan sebagai bahan campuran pembuatan krupuk, terasi atau makanan ternak,
di mana harga jual ketiga produk olahan tersebut tidak setinggi harga chitosan.
Salah satu iklan di internet menyebutkan harga 50 gram chitosan ± $ 23 US.
Belum dimanfaatkannya limbah pengolahan udang dan kepiting sebagai sumber chitosan
boleh jadi disebabkan karena belum dikenalnya industri chitosan secara umum
atau karena tidak ada publikasi yang memuat proses yang dikerjakan secara
sederhana di Indonesia (Kusumawati, 2009).
Setiap
tahun, menurut catatan Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2000, Cold
Storage (perusahaan pengolahan ikan) tanah air
menghasilkan limbah kulit /
kepala udang,
cangkang kepiting dan hewan laut lainnya tidak kurang dari 56.200 metrik ton.
Limbah tersebut terbukti kaya
akan kitin, yang melalui
proses tertentu akan dapat dihasilkan kitosan. Sebagai salah satu negara pengekspor
kepiting, Indonesia tentu saja
berpeluang memproduksi
kitin atau kitosan. Dengan ekspor kepiting (umumnya kaleng) sekitar 4000 ton per
tahun juga berpotensi
menghasilkan kulit sebagai limbah sebanyak 1000 ton per tahun. Limbah
tersebut berpotensi diolah
menjadi kitin, dengan produksi sekitar 1700 ton per tahun. Sebaran
ketersediaan kulit kepiting,
mencakup Sumatera Utara,
Pantai Timur Sumatera, Pantura Jawa, Kalimantan dan Sulawesi Selatan (Agus 2011
dalam Trisnawati et al., 2013).
1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di
atas maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam makalah ini seperti berikut.
1. Apa yang
dimaksud chitosan?
2. Apa sumber chitosan?
3. Bagaimana
cara pembuatan chitosan?
4. Bagaimana
karakteristik chitosan?
5. Bagaimana
penerapan chitosan dalam bidang kehidupan?
6. Apa manfaat penggunaan
chitosan?
1.3
Tujuan
Berdasarkan uraian rumusan masalah
di atas maka dapat ditentukan tujuan dalam makalah ini seperti berikut.
1. Mengetahui
pengertian chitosan.
2. Mengetahui
sumber chitosan.
3. Memahami
cara pembuatan chitosan.
4. Memahami
karakteristik chitosan.
5. Memahami
penerapan chitosan dalam bidang kehidupan.
6. Mengetahui
manfaat penggunaan chitosan.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian
Chitosan
Chitosan adalah suatu
polisakarida yang diperoleh melalui deasetilasi kitin. Perbedaan diantara kitin
dan chitosan terdapat pada derajat deasetilasinya. Chitosan mempunyai derajat
deasetilasi 80-90 %, namun secara umum chitosan dinyatakan apabila derajat
deasetilasinya lebih besar 70 %. Chitosan tidak larut dalam air tapi larut
dalam pelarut asam dengan pH di bawah 6,0. Pelarut yang umum digunakan untuk
melarutkan chitosan adalah asam asetat 1% pada pH sekitar 4,0. Pada pH di atas
7,0 stabilitas kelarutan chitosan sangat terbatas. Pada pH tinggi, cenderung
terjadi pengendapan dan larutan chitosan membentuk kompleks polielektrolit dengan
hidrokoloid anionik menghasilkan gel chitosan yang memiliki kemampuan
menghambat bakteri patogen (antibacteria), menurunkan kadar kolesterol (hypocholesterolemia)
serta mampu memacu kekebalan tubuh (immunostimulant). Sebagai ’kandidat’
pengganti antibiotik, bahan aditif setidaknya harus memiliki sifat antimikroba
(Lin et al., 2009 dalam Harti et al., 2012).
Chitosan
(2-amino-2-deoksi-D-glukopiranosa) adalah senyawa turunan dari chitin
(N-asetil-2-amino- 2-deoksi-D-glukopiranosa) yang terdeasetilasi pada gugus
nitrogennya (Anonim, 1998 dalam
Kusumawati, 2009). Chitin dan chitosan merupakan polimer linier. Deasetilasi yang
terjadi pada chitin hampir tidak pernah selesai sehingga dalam chitosan masih
ada gugus asetil yang terikat pada beberapa gugus N (Kusumawati, 2009).
2.2 Sumber
Chitosan
2.2.1 Kepiting
Kepiting mengandung
persentase kitin paling tinggi (70%) diantara bangsa-bangsa krustasea, insekta,
cacing maupun fungi (Shahidi et al.,
1999 dalam Trisnawati et al., 2013).
2.2.2 Rajungan
Pemilihan rajungan sebagai bahan baku pembuatan
kitosan di dasarkan pada kadar kitin yang tinggi yakni berkisar antara 20-30%
dan bahan yang mudah di dapat karena banyak di konsumsi masyarakat, sedangkan
pemilihan aplikasi sebagai pengawetan ikan di karenakan oleh produksi serta
nilai ekspor ikan yang tinggi di Indonesia (Sedjati, 2006 dalam Silvia, 2014).
2.2.3
Udang
Udang termasuk ke dalam
anggota filum Arthropoda dan termasuk kelas Crustacea. Kerangka
luar udang tersusun atas kitin dan diperkuat oleh bahan kalsium karbonat.
Kandungan kitin dari limbah udang (kepala, kulit, dan ekor) mencapai sekitar
50% dari berat udang (Widodo et al.,
2005 dalam Purwanti, 2014) sehingga
limbah udang ini dapat digunakan sebagai bahan baku penghasil kitin, kitosan,
dan turunannya yang bernilai tinggi (Rachmania, 2011 dalam Purwanti, 2014).
 |
Gambar 1. Udang
(Sumber: Purwanti, 2014)
|
2.3 Cara
Pembuatan Chitosan
Dalam penelitian Kusumawati (2009), proses isolasi
chitin terdiri dari dua tahap, yaitu tahap deproteinasi dilanjutkan tahap demineralisasi
dan pada akhirnya akan mengalami tahap deasetilasi dimana chitin mengalami
transformasi menjadi chitosan. Tahap deproteinasi adalah tahap proses pemisahan
protein yang terdapat pada limbah kulit udang. Setelah tahap deproteinasi dilanjutkan
dengan tahap demineralisasi yang merupakan tahap penghilangan mineral pada
kulit udang yang sebagian besar adalah CaCO3 dan Ca3(PO)4
pada chitin kasar sehingga dihasilkan chitin. Untuk mendapatkan chitosan
dilakukan tahap deasetilasi, dimana derajat diasetilasi yang dihasilkan harus
ada dalam range nilai chitosan standart.
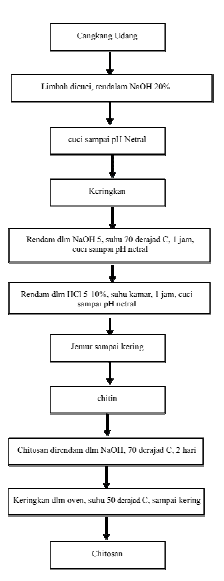 |
Gambar 2. Alur proses pembuatan chitosan dari kulit udang
(Sumber: Swastawati et al., 2008)
|
2.4 Karakteristik Chitosan
Kitosan tidak beracun dan mudah
terbiodegradasi. Kitosan tidak larut dalam air, dalam larutan basa kuat, dalam
H2SO4 dan dalam beberapa pelarut organik seperti alkohol
dan aseton. Kitosan sedikit larut dalam HCl dan HNO3, serta larut
baik dalam asam lemah, seperti asam formiat dan asam asetat (Savitri et al., 2010).
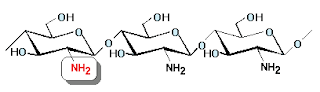 |
Gambar 3. Struktur chitosan
(Sumber: Savitri et al., 2010)
|
Seperti selulosa dan
chitin, chitosan merupakan polimer alamiah yang sangat melimpah keberadaannya di
alam. Namun hal tersebut menunjukkan keterbatasannya dalam hal reaktivitas.
Oleh karena itu, chitosan dapat digunakan sebagai sumber
material alami, sebab chitosan sebagai polimer alami mempunyai karakteristik
yang baik, seperti dapat terbiodegradasi, tak beracun, dapat mengadsorpsi, dan
lain-lain (Kusumawati, 2009).
 |
Gambar 4. Kualitas standar chitosan
(Sumber: Protan Laboraturies Inc, 2004 dalam Fachry dan Sartika, 2012)
|
Kitosan kering tidak memiliki titik lebur. Bila
kitosan disimpan dalam jangka waktu lama pada suhu sekitar 1000F
(37,80C) maka sifat kelarutannya dan viskositasnya akan berubah.
Bila disimpan dalam jangka waktu yang lama dalam keadaan terbuka (terjadi
kontak dengan udara) maka akan terjadi dekomposisi, viskositas larutannya akan
berkurang dan warnanya akan menjadi kekuningan (Utami, 2013).
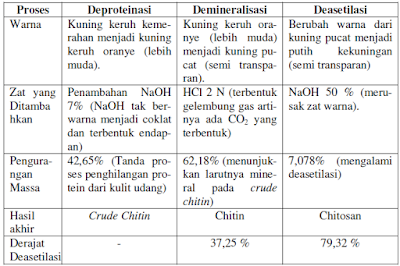 |
Gambar 5. Karakteristik chitin dan chitosan
(Sumber: Widarta, 2004 dalam Kusumawati, 2009)
|
2.5 Penerapan Chitosan dalam Bidang Kehidupan
Kitin dan Kitosan dapat
diaplikasikan dalam bidang industri maupun kesehatan. Beberapa aplikasinya
antara lain di industri tekstil, fotografi, kedokteran, fungisida, kosmetika,
pengolahan pangan dan penanganan limbah. Kitosan juga merupakan bahan baku
pembuatan membran, diharapkan dengan berhasilnya melakukan sintesis produk
kitosan akan menunjang kebutuhan terhadap membran, yang banyak digunakan untuk
berbagai kebutuhan filtrasi atau separasi. Selain itu kitosan dapat berfungsi sebagai
koagulan yang aplikasinya banyak digunakan pada proses pengolahan limbah
(Synowiecki et.al., 2003 dalam Savitri et al., 2010).
 |
Gambar 6. Aplikasi kitin, kitosan dan turunannya dalam industri makanan
(Sumber: Shahidi et al., 1999 dalam Ferdiansyah, 2005)
|
2.5.1 Pangan
Hasil penelitian Satyajaya dan Nawansih (2008) dalam Utami (2013), menyimpulkan bahwa semakin
tinggi konsentrasi kitosan yang ditambahkan pada mie basah, maka akan dihasilkan
mie basah yang mutunya lebih baik dan masa simpannya lebih lama. Pemberian
kitosan pada mie basah dapat meningkatkan nilai gizi dan kualitas mie basah,
dimana pemberian kitosan dapat meningkatkan kadar protein, kadar karbohidrat,
dan menurunkan kadar air pada mie basah. Berdasarkan hasil uji organoleptik
yang dilakukan, diketahui bahwa pemberian kitosan dapat mempertahankan aroma,
warna dan tekstur (Yanti, et al. 2013). Berdasarkan hasil penelitian
Satyajaya dan Nawansih (2008), diketahui bahwa pada penambahan chitosan dengan
konsentrasi 150 dan 200 ppm dengan masa penyimpanan mie basah 0 dan 24 jam,
jumlah total bakteri berkisar antara 2,4 x 105 dan 2,6 x 105 koloni/g. Jumlah
ini masih dibawah SNI No. 01-2987- 1992 untuk mie basah yaitu 1,0 x 106 koloni/g.
Kitosan yang berasal dari limbah
udang dapat digunakan sebagai bahan pengawet daging ayam, tanpa mengubah rasa
dan aroma khas daging ayam. Waktu perendaman terbaik adalah 45 menit pada
kitosan 2%. Sedangkan aplikasi kitosan sebagai bahan pengawet diperoleh kondisi
terbaik pada derajad deasetilasi 70,34%. Kitosan dapat diproduksi dalam
industri rumah tangga karena prosesnya yang sederhana dan mudah dipelajari
(Harjanti, 2014).
2.5.2 Membran Ultrafiltrasi
Chitosan dapat dibuat
menjadi membran ultrafiltrasi. Setelah menjadi serbuk chitosan
dapat langsung dibuat membran
dengan melarutkannya dalam Asam Asetat sebagai pelarut. Sebelumnya
harus dipastikan bahwa cetakan
yang akan digunakan harus
dibersihkan dahulu dengan
menggunakan aseton.
Setelah terbentuk suatu
lapisan film basah cetakan dioven sampai film menjadi kering dimana diperlukan larutan NaOH
4% untuk merendam membran
kering agar
terlepas dari cetakannya. Selanjutnya, agar membran bersih dari alkali diperlukan aquabidestilata
untuk pembilas (Widarta, 2004 dalam Kusumawati, 2009).
 |
Gambar 7. Membran ultrafiltrasi
(Sumber: Kusumawati, 2009)
|
2.5.3 Benang/Kain Antibakteri
Beberapa penelitian
aplikasi kitosan pada benang maupun kain kapas telah dilakukan untuk menghasilkan
produk benang/kain yang bersifat antibakteri. Proses fiksasi kitosan pada
benang/kain kapas dilakukan dengan cara memodifikasi struktur kimia kovalen
serat kapas yang berupa selulosa sehingga terbentuk gugus aldehid dengan menggunakan
oksidator natrium periodat (Yulina et al.,
2014).
2.5.4 Plastik Biodegradable
Plastik
biodegradable dari pati singkong dan kitosan ini menjadi salah satu
alternatif bahan pembungkus. Selain ramah lingkungan karena mudah terurai, juga
memiliki karakteristik awet dan tahan hingga bulan ke-3 dari pemakaian. (Feris,
peneliti muda bidang kimia material dan komposit andalan DPPM UII) (Fachry dan Sartika, 2012).
Bioplastik yang
dihasilkan, yaitu berupa lembaran tipis, transparan
yang tidak tembus pandang dan elastis. Bioplastik dengan
tambahan kitosan yang lebih banyak, tampak sedikit
basah, berbau tajam dan asam. Bau tajam dan asam pada bioplastik disebabkan
oleh asam asetat yang digunakan sebagai pelarut kitosan.
Bioplastik ini mempunyai ketebalan sekitar 70-145 μm
(Hartatik et al., 2014).
 |
Gambar 8. Bioplastik
(Sumber: Hartatik et al., 2014)
|
2.5.5 Pengawetan Ikan
Pengawetan
ikan menggunakan metode Ahmad et al.
(2003) yang diterapkan oleh Mahatmanti et
al. (2011) dalam Silvia et al. (2014) dimana untuk mencari
optimalisasi kitosan sebagai bahan pengawetan kitosan maka kitosan yang
digunakan divariasi konsentrasinya dengan cara melarutkan kitosan (w/v) kedalam
asam asetat 1% (v/v) (Susanti et al.,
2013 dalam Silvia et al., 2014). Sampel ikan kembung (Rastrelliger
sp) dan ikan lele (Clarias batrachus). yang diambil dari tambak,
kemudian ditimbang untuk diketahui massanya. Sampel ikan masing-masing direndam
dalam larutan kitosan dengan konsentrasi yang bervariasi dengan perbandingan 1
kg ikan/1 L larutan kitosan. Penyimpanan dilakukan dengan variasi waktu serta
cara pemberian larutan pengawetan ikan.
2.5.6 Plester Luka
Penelitian
ini bertujuan untuk menguji dan mengembangkan aplikasi penutup luka secara
sistem penghantaran obat melalui potongan kasa (transdermal patch)
dengan modifikasi zat aktif kitosan yang diketahui sebagai alternatif untuk
mengurangi aktivitas bakteri dan mempercepat penyembuhan luka. Sistem
penghantaran obat secara transdermal merupakan salah satu inovasi modern untuk
mengatasi problema bioavailabilitas obat jika diberikan melalui jalur lain
seperti oral (NHF, 2008 dalam Waty,
2012). Oleh karena itu, diperlukan alternatif modifikasi plester kitosan untuk
mempercepat penyembuhan luka ringan pada lapisan epidermis kulit dan diharapkan
dapat mencegah meluasnya luka terinfeksi. Menurut Mutia (2009) dalam Waty (2012), berdasarkan kedalaman
dan luasnya luka, maka luka dibagi menjadi luka stadium I-stadium IV. Plester
luka ini ditujukan untuk luka pada stadium I, yaitu luka yang terjadi pada
lapisan epidermis kulit bagian atas.
2.5.7 Pereduksi Kolesterol Lemak Kambing
Sebanyak 1 kg lemak/gajih yang berasal dari daging kambing
dipanaskan pada suhu tetap 60oC hingga menjadi lemak cair sebanyak
kira-kira 250 ml. Kadar kolesterol dalam lemak mula-mula dianalisis yaitu
sebesar 27,87%. Selanjutnya dilakukan penyerapan kolesterol dengan menggunakan
kitosan. Dalam penyerapan ini dilakukan ekstraksi dengan memasukkan 5 gr
kitosan kedalam beaker glass yang berisi lemak kambing cair sebanyak 50 ml,
diaduk suhu operasi dijaga tetap 60°C, waktu penyerapan divariasi masing-masing
10, 30, 45, dan 60 menit, selanjutnya dilakukan proses penyaringan, filtratnya
diambil untuk dianalisis kandungan kolesterolnya dengan Spektrofotometri (Hargono
et al., 2008).
2.5.8 Pengolah Limbah Industri
Salah satu fungsi kitosan adalah sebagai koagulan dan flokulan.
Bahan koagulasi dan flokulasi ini dipergunakan terutama dalam bidang industri
modern sebagai bahan pengolah limbah industri, oleh karena itu penelitian ini
dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan kitosan dalam mengikat logam berat
yang terdapat di perairan. Hasil penelitian ini diharapkan agar kitosan dapat
digunakan sebagai alternatif lain penurunan kandungan logam berat di perairan.
Pemanfaatan kitosan dari kulit udang yang efektif diharapkan dapat menjadi
salah satu alternatif dalam menanggulangi masalah polusi perairan (Nurhayati
dan Pratiwi, 2016).
2.6 Manfaat
Penggunaan Chitosan
Kitosan sangat
berpotensi sebagai bahan antimikroba, karena mengandung enzim lysosim dan gugus
aminopolysacharida yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Efisiensi daya
hambat kitosan terhadap bakteri tergantung dari konsentrasi pelarutan kitosan
(Wardaniati, et al. 2009 dalam Utami,
2013).
Chitosan memiliki
beberapa manfaat bagi manusia, sehingga merupakan bahan perdagangan yang memiliki
nilai ekonomi yang tinggi. Manfaat chitosan antara lain adalah: (1) dalam
bidang pertanian, chitosan menawarkan alternatif alami dalam penggunaan bahan
kimia yang terkadang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Chitosan membuat mekanisme
pertahanan pada tumbuhan (seperti vaksin bagi manusia), menstimulasi
pertumbuhan dan merangsang enzim tertentu (sintesa fitoaleksin, chitinase,
pectinnase, glucanase dan lignin). Pengontrol organik baru ini menawarkan
pendekatan sebagai alat biokontrol; (2) dalam bidang pengolahan air, chitosan dapat
dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan membran ultrafiltrasi; (3) dalam
bidang makanan, chitosan sudah banyak digunakan dalam komposisi makanan di
Jepang, Eropa dan Amerika Serikat, sebagai perangkap lemak yang merupakan
terobosan dalam bidang diet; dan (5) dalam bidang kesehatan, chitosan digunakan
untuk bakteriostatik, immunologi, anti tumor, cicatrizant, homeostatic dan anti
koagulan, obat salep untuk luka, ilmu pengobatan mata, ortopedi dan penyembuhan
jahitan akibat pembedahan (Kusumawati, 2009).
Limbah udang yang
berupa kulit, kepala dan ekor mengandung senyawa kimia berupa kitin, kitosan,
protein, kalsium karbamat, lemak, air, abu dan lain-lain. Senyawa ini dapat
diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan penyerap logam-logam berat yang
dihasilkan oleh limbah industri. Hal ini disebabkan karena senyawa kitin dan
kitosan mempunyai sifat sebagai bahan pengemulsi koagulasi, reaktifikasi kimia
yang tinggi menhasilkan sifat polielektrilit kation sehingga dapat berperan
sebagai penukar ion (ion exchanger) dan berfungsi sebagai adsorben
terhadap logam berat dalam air limbah (Fachry dan Sartika, 2012).
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari pembahasan diatas dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut.
·
Chitosan adalah suatu
polisakarida yang diperoleh melalui deasetilasi kitin.
·
Chitosan diperoleh dari
cangkan crustacea diantaranya kepiting, rajungan dan udang.
· Proses isolasi chitin terdiri
dari dua tahap, yaitu tahap deproteinasi dilanjutkan tahap demineralisasi dan
pada akhirnya akan mengalami tahap deasetilasi dimana chitin mengalami
transformasi menjadi chitosan.
· Kitosan tidak beracun dan
mudah terbiodegradasi. Kitosan tidak larut dalam air, dalam larutan basa kuat, dalam
H2SO4 dan dalam beberapa pelarut organik seperti alkohol
dan aseton. Kitosan sedikit larut dalam HCl dan HNO3, serta larut
baik dalam asam lemah, seperti asam formiat dan asam asetat
· Kitosan
dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya bidang pangan,
industri maupun kesehatan. Beberapa aplikasinya antara lain untuk pengawet mi
dan ayam goreng, bahan pembuat membran ultrafiltrasi, benang/kain antibakteri,
plastik biodegradable, pengawetan
ikan, plester luka dan pereduksi kolesterol lemak kambing.
· Chitosan
memiliki beberapa manfaat bagi manusia antara lain dalam bidang pertanian,
bidang pengolahan air, bidang makanan dan bidang kesehatan.
DAFTAR PUSTAKA
Fachry, A. R. dan A. Sartika. 2012. Pemanfaatan
limbah kulit udang dan limbah kulit ari singkong sebagai bahan baku pembuatan
plastik biodegradable. Jurnal Teknik Kimia. 3
(18): 1-9.
Ferdiansyah, V. 2005. Pemanfaatan
kitosan dari cangkang udang sebagai matriks penyangga pada imobilisasi enzim
protease. Skripsi. Program Studi
Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
Hargono, Abdullah dan I. Sumantri. 2008. Pembuatan
kitosan dari limbah cangkang udang serta aplikasinya dalam mereduksi kolesterol
lemak kambing. Reaktor. 12 (1):
53-57.
Harjanti, R. S. 2014. Kitosan dari limbah udang sebagai
bahan pengawet ayam goreng. Jurnal Rekayasa
Proses. 8 (1): 12-19.
Hartatik, Y. D., L. Nuriyah dan
Iswarin. 2014. Pengaruh komposisi
kitosan terhadap sifat mekanik dan biodegradable bioplastik. Jurusan
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya.
Kusumawati,
N. 2009. Pemanfaatan limbah kulit udang
sebagai bahan baku pembuatan membran
ultrafiltrasi. Inotek. 13 (2): 113-120.
Nurhayati dan D. Pratiwi. 2016. Pengaruh massa dan
waktu pengadukan kitosan dalam menurunkan timbal dalam air. Seminar Nasional Sains dan Teknologi II. 132-139.
Prihatiningsih,
K., I. Silviana dan N. Wandasari. 2014. Hubungan
perilaku pengolahan limbah ikan asin dengan sanitasi lingkungan kerja fisik
pada industri ikan asin di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) Muara
Angke Pluit Jakarta Utara Tahun 2014. Forum Ilmiah. 12 (1): 77-86.
Purwanti,
A. 2014. Evaluasi proses pengolahan
limbah kulit udang untuk meningkatkan mutu kitosan yang dihasilkan. Jurnal Teknologi. 7 (1): 83-90.
Savitri, E., N. Soeseno dan T. Adiarto. 2010.
Sintesis kitosan, poli (2-amino-deoksi-D-glukosa), skala pilot project dari limbah kulit udang sebagai bahan baku alternatif
pembuatan biopolimer. Prosiding Seminar Nasional
Teknik Kimia “Kejuangan” Pengembangan
Teknologi Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia. 1-10.
Silvia, R., S. W. Waryani dan F. Hanum. 2014.
Pemanfaatan kitosan dari cangkang rajungan (Portonus sanginolentus L.) sebagai pengawet ikan kembung
(Rastrelliger sp.) dan
ikan lele (Clarias batrachus). Jurnal Teknik
Kimia USU. 3 (4): 18-24.
Swastawati, F., I. Wijayanti dan Susanto. 2008. Pemanfaatan
limbah kulit udang menjadi edible coating untuk mengurangi pencemaran
lingkungan. Jurnal Perikanan. 4 (4): 101-106.
Trisnawati, E., D. Andesti dan A. Saleh. 2013.
Pembuatan kitosan dari limbah cangkang kepiting sebagai bahan pengawet buah
duku dengan variasi lama pengawetan. Jurnal Teknik Kimia. 2 (19): 17-26.
Utami,
R. 2013. Pengaruh penambahan kitosan
terhadap jumlah kuman pada mie basah. Artikel
Publikasi Ilmiah. Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu
Kesehatan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
Waty, H. R. 2012. Modifikasi kitosan pada aplikasi
plester luka berbasis kitosan (chitoplast) sebagai transdermal patch antibakteri.
Skripsi. Departemen Teknologi Hasil
Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
Yulina, R., W. Winiati dan C. Kasipah. 2014.
Pengaruh berat molekul kitosan terhadap fiksasi kitosan pada kain kapas sebagai
antibakteri. Arena Tekstil. 29 (2): 81-90.
Oleh: Khoirut Tamam, Andy
Putra Dharmawan, Kiko Rahmad Dilaga K, Muhammad Yusup, Gandy Setiawan, Rizqun
Mubaro, Kholifatul Zahro, Abdi Nugroho, Melynda Dwi Puspita, Nurul Burhanul
Fitroh dan Faizatus Sholihah.

Comments
Post a Comment